Cinta adalah perihal tindakan. Tapi, Zizek membuatnya lain.
aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu
SAYA sebetulnya orang yang begitu saja percaya kata dalam puisi terkenal dari sastrawan Sapardi Djoko Damono: aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kalimat itu adalah sesuatu yang mendobrak suatu unsur kebiasaan. Sewaktu duduk di satu acara bersama, kemenakan SDD, yaitu Jokpin alias Joko Pinurbo berkata, “mencintai dengan sederhana adalah sesuatu yang paling tidak sederhana.” Saya pikir ucapan itu ada benarnya.
Lucunya, dalam cinta, banyak hal yang selalu dikaitkan dengan suatu upaya timbal balik. Jika meminjam frasa Marx, ia pernah berkata: Jika Anda mencintai tanpa membangkitkan cinta sebagai balasannya – yaitu, jika cinta Anda sebagai mencintai tidak menghasilkan cinta timbal balik; jika melalui ekspresi hidup diri Anda sebagai orang yang penuh kasih, Anda tidak menjadikan diri Anda orang yang dicintai, maka cinta Anda tidak berdaya – sebuah kemalangan. Sungguh ucapan yang sangat tidak marxis dari seorang Marx!
Hal ini seolah-olah ditampik oleh seorang penyair kenamaan Indonesia, Sapardi Djoko Damono (selanjutnya disingkat SDD). Bukan tanpa sebab, sewaktu duduk di bangku SMA, orientasi kita terhadap sesuatu yang absurd bernama cinta telah mencapai titik kulminasi. Lebih dari itu, perasaan itu membuncah ketika orang tersebut bereaksi terhadap rasa ini. Ada perasaan getir, berdebar, sekaligus bahagia. Artinya, kita ada di dalam satu perasaan berbunga-bunga ketika melihat orang yang kita cintai. Sulit rasanya membayangkan suatu perasaan yang sarat akan kasih sayang, tanpa berharap timbal balik dari objek cinta kita.
Paling banter, jika memang timbal balik itu tak terjadi, nelangsa-lah jawabannya. Saya pikir awalnya itu sesuatu yang alami, karena pengharapan untuk dicintai sudah aksiomatik. Tapi, bayangkan jika begini: mencintai tanpa berkata, mencintai tanpa kata-kata, mencintai dalam ketiadaan kata-kata. Mungkinkah? Atau memang secara haqul yakin, kita sudah mempersepsikan keadaan di mana cinta harus berkata-kata. Tanpa kata-kata, apakah cinta bukan sebuah cinta?
Untuk itu, biarkanlah Jacques Lacan bersabda. Seorang psikoanalis nyentrik asal Prancis membagi tiga kategori terhadap resepsi realitas. Ia membagi orde riil, simbolik, dan imajiner. Sederhananya, ketiganya meliputi aspek realitas sebelum dan setelah insan mengenal bahasa.
Dalam tatanan riil, Lacan mendefinisikan sebuah kondisi yang belum terjamahkan oleh bahasa. Selebihnya, itu masuk ke dalam tatanan simbolik, yang berarti tatanan simbolik adalah realitas atau segala hal yang sudah dikenai oleh bahasa, sementara the imajiner adalah jurang yang memisahkan penamaan yang riil oleh simbolik.
Yang bermasalah di titik ini adalah ketika manusia terlempar ke dalam mekanisme simbolik, ia terjerembap ke dalam ruang yang menjahit torso manusia beserta segala semesta pikirannya ke dalam point de capiton.[1] Implikasinya, ia menjadi subjek yang serba kekurangan, karena Yang-Simbolik hadir sebelum subjek, jadi mau tak mau, ia ada di dalam kungkungannya atau center of narrative gravity[2]. Ini juga berakibat pada keberadaan Yang-Lain.
Pengalaman cinta juga memiliki modus operandi yang kurang lebih serupa. Bagi orang kebanyakan, cinta bermakna apabila bekerja. Aktivasi cinta dinilai dari sebuah proses timbal balik. Baginya juga merupakan suatu pemenuhan aspek diri yang dikastrasi.[3] “To really love someone is to believe that by loving them, you’ll get to the truth about yourself.” Subjek menjadi sesuatu yang berkekurangan dan selalu berusaha untuk mencari rangkaian yang hilang dalam diri orang lain, untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa everyday objects are symbolized in the sense that they mean something, they have a signification ada benarnya.[4]
Hal ini kemudian diradikalisasi oleh Slavoj Zizek beberapa dekade kemudian. Ia mengusahakan untuk mewujudkan suatu ruang yang memungkinkan tindakan yang tidak terkatakan.[5] Baginya, kesadaran diri hanya harus menjadi sadar betapa Ketiadaan yang muncul pada Kehendak tertentu sebagai ancaman eksternal yang abstrak dan menentang yang bertepatan dengan kekuatan negativitasnya; ia harus menginternalisasikan kekuatan negativitas ini dan mengakui di dalamnya esensinya sendiri, inti utama dari adanya.[6]
Kembali lagi ke dalam duduk persoalan cinta. Kesederhanaan cinta yang dimaksud SDD, paling tidak dalam hemat saya, adalah mengenai sesuatu yang tak terbahasakan.
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan
yang menjadikannya tiada
Sesederhana itu cinta bagi SDD. Bilamana mencinta, seseorang dengan kesederhanaan pasti menginternalisasikan kekuatan negativitas dan mengakui di dalamnya, esensinya sendiri. Bagi subjek, momen ketakterbahasakan cinta adalah momen yang sangat sakral.
Perlu dicatat, di sini cinta yang tak terbahasakan bukan serta-merta cinta yang penuh dengan adegan dramatis versi FTV ataupun sinetron. Cinta yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada sebuah mekanisme operasi cinta yang melampaui segala simbol, yang dibetot oleh bahasa. Bukan juga cinta yang penuh dengan pengorbanan atau segala macamnya.
Cinta yang sederhana, berkesinambungan dengan mistifikasi kehampaan dalam diri subjek. Alih-alih didorong oleh, katakan saja, pengorbanan atau hasrat lain, kehampaan ini menjadi variabel penentu. Mesti juga diperhatikan bahwa Kejadian dengan basis semacam ini memperhitungkan mekanisme sebab akibat. Kehampaan harus menjadi sebab utamanya. Dalam kehampaan, ego dikubur hidup-hidup, sehingga subjek menjadi entitas tunggal yang otentik yang bukan lagi berbicara dalam wilayah praktis atau pragmatis. Ketika pembahasaan dilampaui, sebab bagi Zizek, pergeseran dari ego menuju subjek adalah esensi dalam radikalismenya.[7]
Wilayah yang melampaui kata mentransformasikan diri subjek. Dalam hal percintaan, tindakan ini adalah tindakan yang paling otentik dan frontal. Makna tindakan menurut Žižek, harus muncul dari suatu tatanan yang tidak berdasar yang melampaui tatanan simbolik.[8] Dengan menggebuk dirinya, dengan menyeruak untuk memilih sebuah pilihan gila, tindakan itu boleh jadi menghasilkan sebuah pergeseran koordinat yang sama sekali revolusioner.[9]
Dalam hal percintaan, absolutisme dalam wujud timbal balik menjadi denominator utama. Bilamana tidak, siap-siap untuk dilanda ejekan, ledekan, hingga kepedihan. Ada sebuah konsep yang sangat provokatif berkaitan dengan kasih atau agape. Hal ini bisa dipetik dari Allah ketika menahbiskan Yesus, supaya manusia dapat mengakses transendensi.[10]
Ketika Allah mengumumkan pengiriman putra yang tunggal yang termanifestasikan lewat daging demi mentransmisikan sebuah universalitas baru. Tindakan Allah yang demikian melahirkan sebuah asumsi yang sangat spesial. Destruksi ego di sini adalah tindakan otentik yang melahirkan sebuah ruang kosong bagi kemunculan sebuah subjek yang baru.
Dengan menebas bebas dirinya dari obyek berharga yang kepemilikkannya justru membuatnya tetawan oleh sang musuh, subyek pun merebut ruang bagi tindakan bebas. Tidakkah sikap radikal ‘menyerang diri sendiri’ merupakan perwujudan subjektivitas yang sedemikian?[11]
Kembali lagi ke duduk persoalan mengenai cinta. Kayu yang dilalap api dan awan yang mengalami presipitasi menandai untaian kata-kata yang tiada sempat terkatakan. Di situlah kehampaan hadir, karena dengan satu-satunya alasan itu, subjek bisa melampaui segala jenis tanda dalam bahasa. Dalam kehampaan dan ketiadaan pula, cinta bisa diperam. Ia hadir di dalam suatu kondisi keberanian untuk menjemput Kejadian yang melampaui kata. Dari situ, ‘subjek muncul pada titik kekosongan yang sama sekali tidak bermakna yang dibawa oleh sebuah negativitas yang meledakkan kerangka pertukaran yang seimbang. Dengan cara ini, kita pergi dari kebebasan mutlak (dari masyarakat revolusioner).’[12]
Modus operandi cinta ditempatkan dalam kerangka radikal menjadi sebuah titik tolak dari perjalanan ideal. Alih-alih berharap menjadi begitu-begitu saja, subjek harus sadar bahwa patahan yang dihasilkan dari unrequited love adalah momen yang berharga. Sebab, di titik itu, hadir sebuah kesempatan untuk menafikan sebuah struktur simbolik yang diagung-agungkan.
Tindakan otentik dalam puisi Aku Ingin mengandaikan sebuah kehancuran subjek. Dilalap api dan menjadi hujan adalah bahasa metaforis yang menggambarkan luruhnya subjek. Demi apa? Bagi seorang radikalis cinta, jawabannya harus ‘bukan apapun’. Jika kita menjawab demi orang yang kita cintai, demi kebahagiaan, atau segala tetek bengek, maka kita telah menafikan prasyarat dasar radikalisme, karena terkungkung oleh ruang simbolik itu sendiri.
Cinta dalam sajak versi sederhana ala Sapardi Djoko Damono sejalan dengan radikalisme. Dalam arti luas, cinta yang mendekap realitas kekosongan. Tentu saja ini bukan bermaksud untuk mengatakan cinta yang tidak terbalaskan. Lebih dari itu, cinta radikal atau yang sederhana itu melampaui segala bentuk resiprositas pelaku-pelakunya, yaitu suatu kesederhanaan yang utuh dan murni, yang hadir tanpa bahasa dan wicara.
Act as if you believe and belief will come by itself!
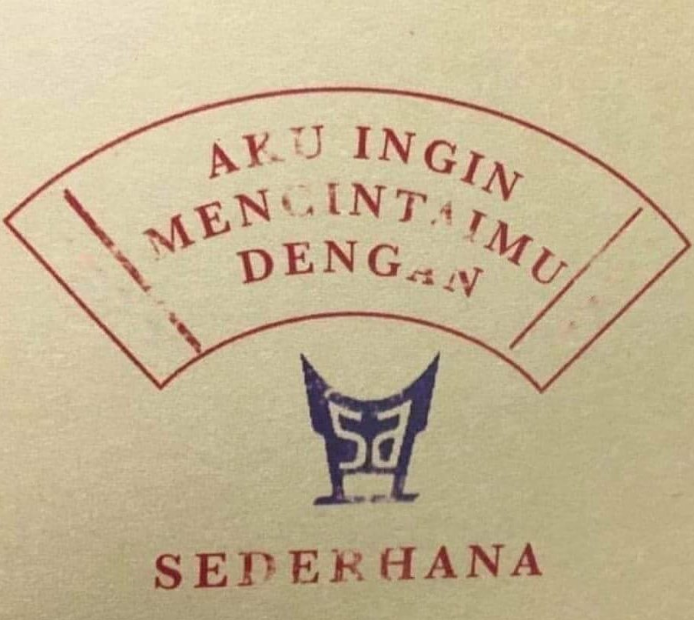
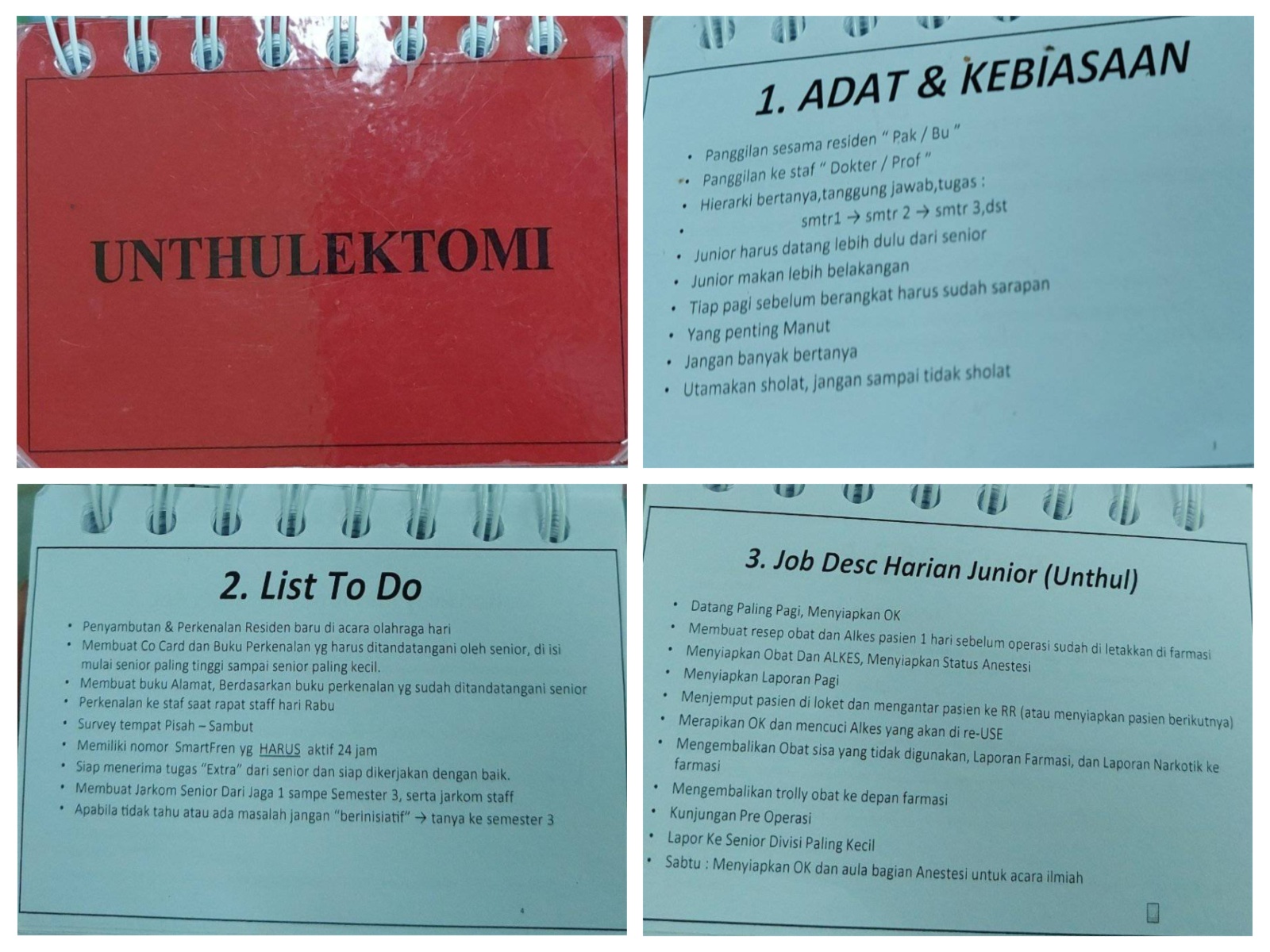

Comments
Leave a Comment