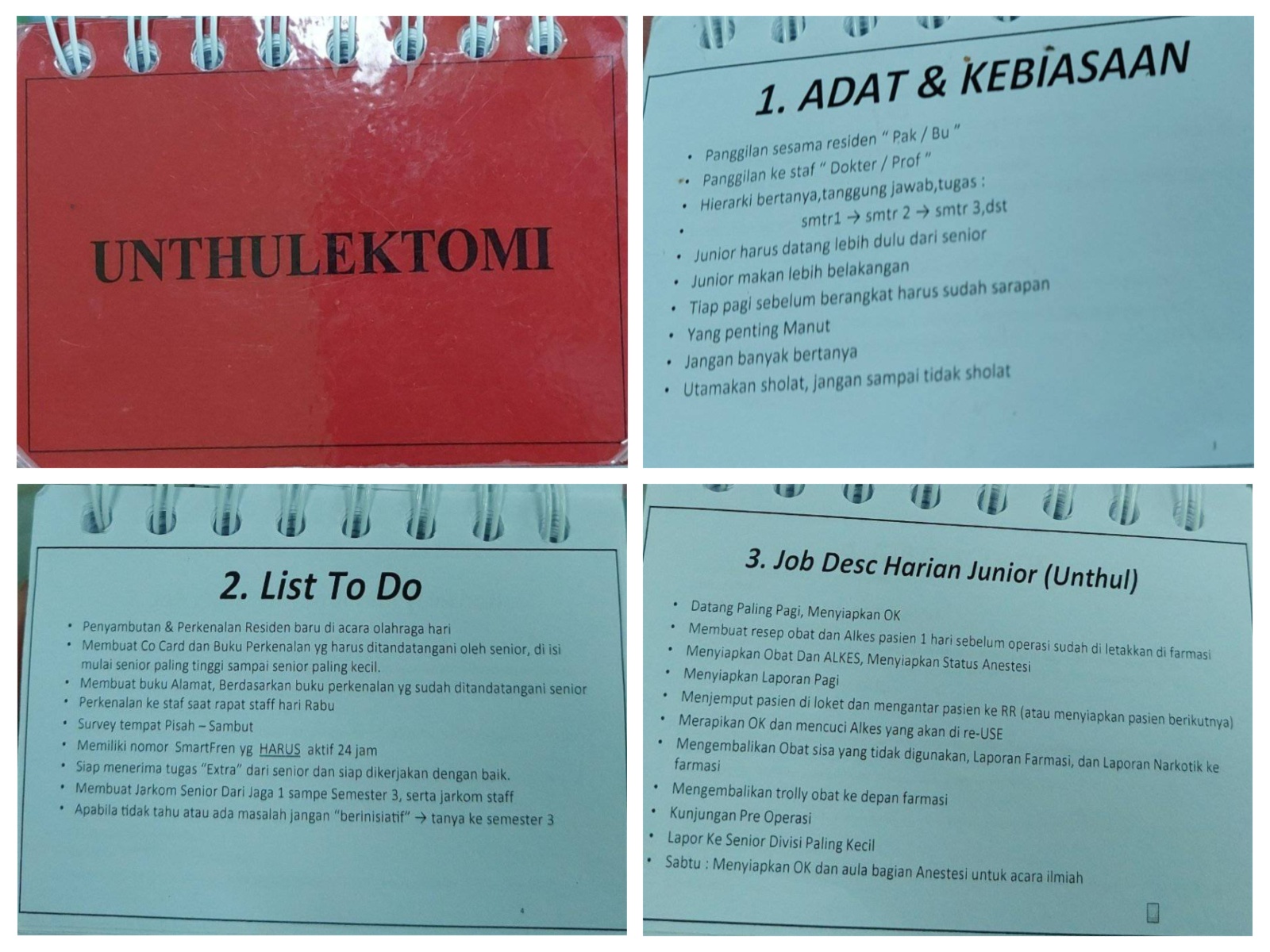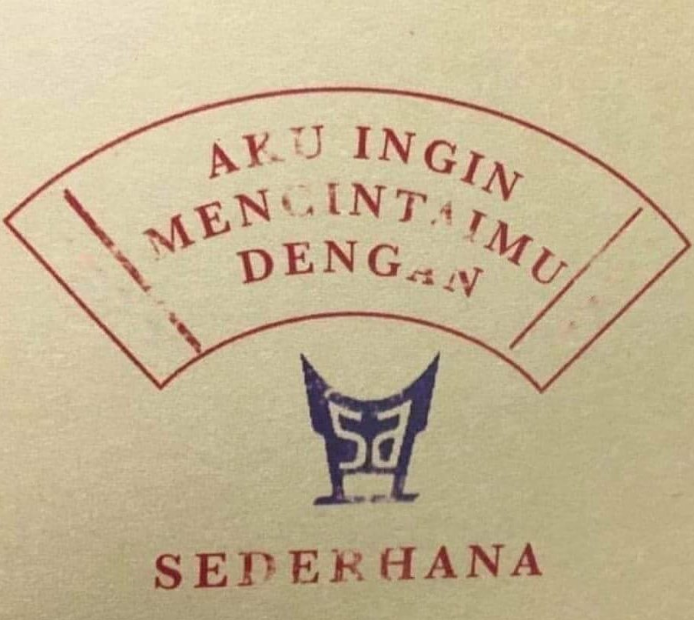Amok adalah kata serapan bahasa Inggris dari bahasa Melayu. Ini mendefinisikan sebuah keadaan yang suram dan penuh dengan ungkapan emotif. Tulisan ini mengupas kecenderungan kontemporer terhadap amok.
DALAM sejarah kontemporer, sudah banyak kejadian yang mengharuskan sistem yang baik, dengan sendirinya runtuh akibat emosi amarah atau amok. Dari mulai rezim teror yang menerkam anak-anaknya sendiri, hingga bolshevik yang disingkirkan ke Gulag. Benarlah adagium yang disampaikan Hermawan Sulistyo: korban dari revolusi adalah anak-anak dari revolusi itu sendiri. Rasa-rasanya memang tragis mendengar sejarah yang seolah-olah bisa dimanipulasi oleh kelompok atau individu yang bengis tapi begitulah adanya. Saya cukup percaya bahwa gerak sejarah tidak pernah lurus, melainkan siklis.
Dari proses itu, hal yang dominan dalam masyarakat adalah fenomena amok. Kata ini berakar pada bahasa Portugis, yang berarti amuco atau amuoco. Secara etimologis, ini artinya ‘penyerangan secara keras’. Ingatan sejarah selalu dikaitkan dengan amok, dan ini yang paling penting: amok hampir selalu lekat dengan persoalan pemretelan apapun yang sah. Ingatkah ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan karena kemarahan terhadap Perjanjian Versailles karena di pikirannya, Jerman diinjak-injak harkat martabatnya dengan membayar hutang akibat kalah perang. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Emosinya dari situ mulai membuncah. Termasuk dengan mengkambing hitamkan orang Yahudi.
Akibatnya mengerikan. Berjuta jiwa masuk ke dalam kamar gas. Sebagian besar lainnya harus mati di medan perang. Sebagian besar lainnya harus juga mengungsi dan menjadi yatim piatu. Semua ini mulai dari satu ledakan emotif dari Hitler, tentu saja bersama kroco-kroconya. Kecenderungan hari ini juga relatif serupa. Tentu saya tidak berdoa supaya Hitler ada kembali, tapi letupan emotif mulai bisa terlihat di mana-mana.
Beberapa di antaranya adalah kebangkitan sentimen ekstrem kanan menguat dengan mengaduk-aduk sentimen rasial yang menyasar imigran. Di Timur Tengah, konflik Israel dan Palestina didasari pada kecenderungan emotif yang eksesif. Di Asia, misalnya, narasi amok juga terlihat jelas dalam tingkah laku penguasa di India yang menaklukan Muslim. Ini terjadi nyaris di mana-mana. Dari skala paling makro hingga mikro, ketika menghadapi amok, segala aturan menjadi luruh. Dari hal yang paling sederhana: moral, visi, misi, imaji, dan sebagainya runtuh apabila meresap pada amok.
Fenomena kebangkitan kanan, misalnya, mengandaikan ada emosi yang diaduk-aduk di sejumlah titik di Eropa. Ketika serangan terhadap Charlie Hebdo dan pembunuhan Samuel Paty, Marine Le Pen, seorang sempalan partai sayap kanan Rassemblement Nationale kerap kali melontarkan sebuah komentar yang menstigmatisasi Islam. Ia pernah berkata bahwa, “Ada beberapa yang percaya bahwa sekularisme dan Islam tidak cocok. Politisi ekstremis sayap kanan di hampir seluruh negara Eropa mulai dari barat hingga timur benua tersebut mengecam tindakan dan tetap berpegang teguh pada prinsip kebebasan. Ia di kesempatan lain menambahkan, “Serangan ini adalah akibat dari ideologi kejam yang saat ini tengah membantai ribuan orang di seluruh dunia.”1
Hari ini, Financial Times mencatat tren serupa, mengingat benua tersebut akan memilih wakilnya di Parlemen kawasan. Sebagian politisi ekstrem kanan mengkorelasikan gelombang imigran dan aksi teror. Mulai dari Yunani (New Democracy), Austria (Heinz-Christian Strache), Spanyol (Plataforma per Catalunya), Jerman, Denmark, dll menuduh imigrasi tahun 2015 hingga kini adalah salah satu penyebab utamanya. Ini tercermin dari sikap Bloc Identitaire, sebuah kelompok sayap kanan menanggapi dengan mengeluarkan sebuah artikel bertajuk, “Tidak ada yang bisa berpura-pura memerangi jihadisme tanpa mempertanyakan imigrasi besar-besaran dan Islamisasi.”2
Politisi dari partai sayap kanan Jerman AfD (Alternative für Deutschland), Beatrix Von Storch berkomentar dengan nada yang keras, karena banyaknya imigran dengan berkata, “Apakah kita sekarang menenangkan gerombolan Muslim pemerkosa barbar?”3.
Lebih lagi, 7 Oktober 2023 berbuntut panjang hingga hari ini. Semua mata tertuju pada tindakan kedua belah pihak, Israel dan Hamas yang dianggap mewakili otoritas Palestina. Kemarahan itu letaknya jelas, pada alur sejarah di Timur Tengah. Semua dilampaui dalam kemarahan itu. Tak ada lagi HAM, Camp David, dan nota-nota Dewan Keamanan PBB. Hingga kini, sandera dan korban pun berjatuhan. Al Jazeera per Mei 2024, mencatat bahwa setidaknya korban jiwa dari kedua belah pihak mencapai 38.000an jiwa (36,743 orang Palestina dan 1,139 orang Israel).4
Gejala ini telah diprediksi oleh Peter Sloterdijk. Ia menuliskan adagium yang diplesetkan dari Descartes, yaitu I irritate, therefore I am.5 Baginya, ingatan adalah satu produk dari jaringan generasi yang memperkenalkan sekuel mengenai rasa sakit. Oleh karena itu, sensibilitas nasional dan gejala neurosis diturunkan dari ingatan akan rasa sakit yang menciptakan suasana traumatik. Ini berakibat pada sebuah pengaruh bahwa konsep keabadian menjadi diasosiasikan dengan hukuman dan penyiksaan, yang dihasilkan dari sebuah ingatan akan ketidakadilan sehingga memantik celah-celah kemarahan.6
It is not merely the ability to counteract the immediate disappearance of the lived moment by “retention,” that is, an inner, automatic function of holding onto temporal consciousness. lt is also connected to a saving function that enables the coming back to virtual tapies and scenes. Memory is a result of the generation of networks through which the new introduces itself compulsively, and like an addiction, into older episodes of pain. 7
Sloterdijk lebih lanjut mengemukakan bahwa terdapat mekanisme ‘tabungan kemarahan’. Operasionalisasinya sederhana karena secara empiris melibatkan ingatan akan trauma nasional sekaligus juga kewajiban untuk membalas pembuat kepedihan itu. Seringkali, kemarahan ini dihubungkan dengan aspek-aspek transenden, yaitu, pada aspek-aspek keilahian.8 Untuk itu, harus ada mekanisme untuk menyembuhkan rasa sakit.
Peradaban selalu gandrung dengan memori kolektif akan sebuah rasa sakit. Dalam mekanisme mulusnya amok, mekanisme nilai tukar dalam institusi seperti bank dipergunakan. Rasa sakit secara kolektif ditabung dalam suatu kurun waktu. Akibatnya adalah pembalasan yang sudah diakumulasi melalui transformasi sejarah yang panjang. Amarah itu dipupuk dari ingatan-ingatan sejarah.9
Melalui narasi dan juga tindakan konkret, amarah ini meletup sejalan dengan sebuah transformasi sosial. Dalam Age of Anger, Pankaj Mishra menjelaskan bagaimana kemarahan itu ditabung dalam waktu. Salah satunya, adalah dosa besar yang diakibatkan pencerahan ala kawasan Atlantik Barat. Era ini mengandung sebuah pembalikan besar-besaran, dengan meliputi segala aspek kehidupan yang paling ‘canggih’.10
Peradaban barat selalu gandrung dengan optimisme semacam itu. Para pentolannya hendak mempreservasi bentuk-bentuk otonomi manusia lewat kemajuan. Nada-nadanya pun selalu bercorak triumfalistik, salah satunya adalah dengan mendikte berbagai entitas politik maupun sosial untuk ikut dalam standarnya. Mereka rela untuk menyatakan perang demi tegaknya ‘peradaban’. Titik baliknya adalah dua revolusi, yaitu industri dan sosial-politik di Prancis. Dari situ, seolah-olah ada ketunggalan dalam proses sejarah. Semua harus melibatkan utilitas (berkaitan dengan revolusi Industri) dan egalite, fraternite, dan liberte (berkaitan dengan Revolusi Prancis).
ak jarang, dengan melibatkan mekanisme kekerasan yang barbar, yang terpenting adalah kemajuan dan modernitas. Salah seorang apologis terhadap proses ini merupakan Voltaire, penulis dan pemikir kenamaan asal Prancis.’11 Ketika menjelaskan tentang Petrus Agung di Rusia, yang rela membunuh sekian banyak jiwa, tetapi ‘ia [Petrus Agung] berhasil membangun jembatan [simbol kemajuan]’.
Ada aksi, pasti ada reaksi. Tak sampai satu dekade, mulai bermunculan poros pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, yang kemudian diikuti dengan semangat romanitisisme ala Jerman. Gerakan itu hendak mempertanyakan kesahihan makna ‘kemajuan’ yang diagung-agungkan itu. Gerakan ini secara praktis hal ini kembali lagi melibatkan interioritas batin manusia, dengan eksaminasi. Bagi mereka, cara berpikir simplistik ala modernitas mengakibatkan serangan fatal terhadap kondisi batin dan amour propre.12
Salah satu upaya untuk menentang gerakan kemajuan adalah dengan kekembalian pada Kultur dan Volk. Dua hal itu bisa secara langsung ataupun tidak membumikan perasaan dan eksistensi manusia pada dirinya sendiri, sesuai dengan kebudayaan dan kenegaraan. Hal ini dipercaya dapat mengembalikkan kemurnian yang belum terdistorsi oleh arus kemajuan. Akibatnya, sensasi tribalistik kembali ditemui. Arus kemarahan mulai terasa dalam diri orang-orang yang menolak mengikuti kemajuan.13 Secara sederhana, ini yang kemudian berbuntut panjang kepada pencobaan untuk membalikkan tatanan yang sudah direnggut dan distandarisasi menggunakan parameter yang ‘itu-itu saja’.Beragam peristiwa merupakan cerminan dari realitas yang taken for granted. Dinamika semacam ini bisa berhubungan dengan aspek-aspek ketahanan dan identitas yang saling menyerang. Mau bagaimanapun, amok menjadi tak terhindarkan.
- Alberto Nardelli, “Angela Merkel’s Stance on Refugees Means She Stands Alone against Catastrophe | Alberto Nardelli,” The Guardian (The Guardian, 29 November 2017), https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/08/angela-merkel-refugee-crisis-europe
- VICE Staffs, “How the Far Right and Conservatives of Europe Reacted to the ‘Charlie Hebdo’ Massacre,” http://www.vice.com, 8 Januari 2015, https://www.vice.com/en/article/kwpvpy/how-europes-conservatives-reacted-to-the-charlie-hebdo-massacre.
- Jeffrey Gedmin, “Right-Wing Populism in Germany: Muslims and Minorities after the 2015 Refugee Crisis,” Brookings (Brookings, 24 Juli 2019), https://www.brookings.edu/research/right-wing-populism-in-germany-muslims-and-minorities-after-the-2015-refugee-crisis/.
- https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker.
- Thompson, D. & Martinez, C. (2024). "Digital democracy and policy innovation." Technology and Governance Review, 12(4), 223-245.
- Rage and Time, 46.
- Ibid.
- Ibid, 71.
- Ibid, 87.
- Ibid.
- Definisi ‘canggih’ berkaitan luas dengan cara hidup yang bercorak positivis (membalikkan tatanan metafisis, menentang otoritas keagamaan, dll).
- Age of Anger, Voltaire, 95
- Rousseau pertama kali mengemukakan istilah ini untuk menjelaskan mekanisme kondisi self-love dan self-esteem, alih-alih istilah ‘peradaban‘ yang serba kering.
- Salah satu akibat paling mengerikan dari kekembalian pada tribalisme adalah kemunculan sosok Hitler dan Mussolini, yang banyak terinspirasi dari kecenderungan emotif akibat arus modernisasi.